HUKUM - Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar masalah hukum, melainkan sudah menjadi wabah yang menggerogoti moralitas, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi tidak hanya meningkat dalam jumlah tetapi juga dalam kualitasnya—makin kompleks, makin terstruktur, dan melibatkan aktor-aktor besar dalam pemerintahan dan sektor swasta. Namun, meskipun urgensi penanganannya semakin tinggi, pemerintah dan DPR RI masih setengah hati dalam mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, sebuah instrumen yang sejatinya dapat mengefektifkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Jika kondisi ini terus berlanjut, haruskah rakyat turun tangan untuk menghukum koruptor secara massal?
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Korupsi di Indonesia
Jika kita melihat data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, Transparency International melalui indeks persepsi korupsi (CPI) menempatkan Indonesia dalam posisi yang stagnan atau bahkan mengalami penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada dua hal yang perlu disoroti di sini: pertama, meningkatnya jumlah kasus yang terungkap dan, kedua, meningkatnya kualitas korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar dengan modus yang semakin canggih.
Korupsi yang dilakukan pejabat negara kini bukan hanya sebatas suap atau gratifikasi, tetapi juga melibatkan skema keuangan yang kompleks, pencucian uang lintas negara, dan penyalahgunaan kebijakan untuk menguntungkan segelintir elite. Salah satu contoh terbaru adalah kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret pejabat tinggi dan pengusaha dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Kasus-kasus lain seperti dugaan korupsi di sektor pertambangan, proyek infrastruktur, hingga mafia peradilan semakin menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya sistemik, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan kekuasaan.
Mandeknya UU Perampasan Aset: Bukti Ketidaktegasan Pemerintah dan DPR
Di tengah masifnya korupsi, instrumen hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan memulihkan aset negara yang dirampok oleh para koruptor. Salah satu instrumen yang dinantikan adalah Undang-Undang Perampasan Aset, yang seharusnya dapat mempercepat penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Namun, hingga kini, UU Perampasan Aset belum juga disahkan oleh DPR dan pemerintah. Berbagai dalih digunakan untuk menunda pembahasannya, mulai dari alasan teknis hingga kepentingan politik. Padahal, banyak negara telah membuktikan bahwa perampasan aset adalah langkah efektif dalam memberantas korupsi. Filipina, misalnya, telah menggunakan mekanisme ini dalam kasus korupsi mantan Presiden Ferdinand Marcos, yang memungkinkan negara untuk mengambil kembali miliaran dolar yang disimpan di luar negeri. Lalu, mengapa Indonesia masih ragu?
Alasan yang paling mungkin adalah karena UU ini akan langsung mengancam banyak elite politik dan pejabat yang selama ini menikmati hasil korupsi. Jika disahkan, UU ini akan memudahkan negara dalam menyita harta yang tidak wajar dari pejabat tanpa harus melalui proses pengadilan yang berbelit-belit. Dengan kata lain, banyak pihak di DPR dan pemerintah yang merasa UU ini justru menjadi ancaman bagi kepentingan mereka sendiri.
Haruskah Rakyat Menghukum Koruptor Secara Anarki?
Ketika pemerintah dan DPR tidak serius dalam memberantas korupsi, wajar jika muncul pertanyaan: apakah rakyat harus turun tangan dan menghukum koruptor secara massal? Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh di mana rakyat yang frustrasi terhadap korupsi akhirnya mengambil tindakan sendiri, baik dalam bentuk protes besar-besaran, revolusi, hingga penghukuman langsung terhadap pejabat yang korup.
Di Indonesia, beberapa peristiwa menunjukkan bahwa kemarahan rakyat terhadap korupsi bisa berujung pada aksi spontan yang ekstrem. Salah satunya adalah kasus mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, yang sempat hampir dihakimi massa karena dugaan korupsi yang merugikan rakyat kecil. Kasus lain adalah gerakan sosial yang menuntut pemboikotan terhadap produk-produk atau institusi yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini membuktikan bahwa jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, maka kemungkinan tindakan main hakim sendiri bisa semakin besar.
Namun, menghukum koruptor secara massal bukanlah solusi yang ideal dalam negara hukum. Jika rakyat mulai mengambil tindakan sendiri tanpa melalui jalur hukum, maka yang terjadi bukanlah keadilan, tetapi kekacauan. Oleh karena itu, tekanan publik harus diarahkan pada gerakan yang lebih strategis, seperti memperkuat gerakan masyarakat sipil, menuntut transparansi anggaran, mendukung KPK dan lembaga antikorupsi lainnya, serta menolak calon pemimpin yang memiliki rekam jejak korupsi dalam pemilu.
Korupsi di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sayangnya, respons pemerintah dan DPR masih setengah hati, terlihat dari lambatnya pengesahan UU Perampasan Aset. Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar jika muncul gagasan bahwa rakyat harus turun tangan untuk menghukum koruptor secara langsung. Namun, tindakan main hakim sendiri bukanlah solusi yang tepat dalam negara hukum. Yang diperlukan adalah tekanan publik yang lebih kuat agar pemerintah dan DPR tidak lagi bersembunyi di balik kepentingan mereka sendiri. Hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Jakarta, 08 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi


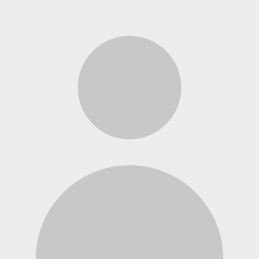 Updates.
Updates.






























